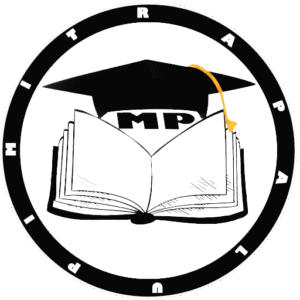Bapak Paus
~ Okky Madasari ~
Bapak, selamat datang
di tanah kaum beriman
di negeri berwajah suci
di ibu kota dosa-dosa
yang tersembunyi
dalam lantunan puja-puji.
Bapak, lihatlah kami
domba-domba Tuhan
yang lapar dan kehausan
mengantri janji surgawi
menanak ulang iman kami
untuk sarapan esok pagi.
Bapak, intiplah mereka
membangun kerajaan surga
di atas galian tambang
di tepi sungai air mata
mementaskan sandiwara
di panggung neraka dunia.
— 3 September 2024 —
Selamat datang di tanah kaum beriman—begitu puisi “Bapak Paus” karya Okky Madasari dibuka, seolah menyambut sosok Paus Fransiskus di tengah-tengah masyarakat yang gemar menyembunyikan dosa di balik topeng religiusitas. Ini bukan sekadar sapaan biasa, melainkan awal dari sebuah kritik tajam yang dengan halus diselipkan dalam rangkaian kata. Bukan sembarang sambutan, puisi ini justru mengajak kita untuk melihat realitas sosial yang penuh dengan ironi dan kemunafikan. Tanah yang diaku sebagai beriman ternyata dipenuhi dengan dosa-dosa yang tertutup rapi oleh lantunan puja-puji. Dalam puisi ini, Okky Madasari dengan cerdik membongkar kepalsuan yang menyelimuti wajah masyarakat kita.
Puisi ini memotret realitas yang sering kali terabaikan: bagaimana agama bisa berubah menjadi instrumen yang menutupi kenyataan pahit kehidupan sehari-hari. Di negeri yang katanya berwajah suci, dosa-dosa disembunyikan di balik keagungan ritual dan upacara. Madasari menggunakan bahasa yang tajam namun indah untuk mengungkapkan kontradiksi antara tampilan luar dan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Dalam bait pertama saja, kita sudah diajak merenungkan bagaimana iman yang seharusnya menjadi landasan moral malah sering kali dijadikan tameng untuk menutupi kekurangan dan dosa.
Pada bait berikutnya, Madasari mengalihkan fokus pada domba-domba Tuhan, yakni umat yang lapar dan haus akan janji-janji surgawi. Di sini, Madasari menyoroti bagaimana janji-janji religius yang sering kali dilontarkan justru memperpanjang penderitaan umat. Mereka terus-menerus mengantri untuk mendapatkan ‘iman’ yang seolah-olah menjadi sarapan esok pagi, namun kenyataannya hanya menunda rasa lapar mereka akan keadilan dan kebenaran. Iman di sini digambarkan sebagai sesuatu yang disajikan ulang, bukan untuk memenuhi kebutuhan rohani, melainkan lebih sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Dengan sangat halus, Madasari mengkritik bagaimana agama bisa disalahgunakan sebagai alat penundaan, bukan pencerahan.
Bait terakhir puisi ini adalah yang paling menggugah. Madasari meminta Paus untuk mengintip bagaimana “mereka”—mungkin para elit atau penguasa—membangun kerajaan surga di atas galian tambang dan tepi sungai air mata. Imaji yang digunakan di sini sangat kuat: sebuah “panggung neraka dunia” di mana sandiwara keagamaan dipentaskan di atas penderitaan orang-orang biasa. Dalam gambaran ini, Madasari tidak hanya menunjukkan ironi di balik pembangunan yang diklaim sebagai ‘kerajaan surga’, tetapi juga bagaimana proses tersebut dilakukan dengan mengorbankan mereka yang berada di lapisan terbawah masyarakat. “Sandiwara” yang disebut dalam puisi ini menjadi simbol dari kepalsuan yang terus dipertahankan oleh mereka yang berkuasa, sementara ‘kerajaan surga’ yang dijanjikan tidak pernah benar-benar menjadi kenyataan bagi mereka yang berada di bawah.
Yang jarang disadari, atau mungkin belum banyak diketahui orang, adalah bahwa puisi ini bukan hanya kritik terhadap masyarakat atau penguasa, tetapi juga tantangan bagi Paus Fransiskus sendiri. Dalam konteks kunjungan Paus ke Indonesia dan bagaimana dia dikenal sebagai pemimpin yang meruntuhkan batas-batas tradisi untuk melayani yang termarjinalkan, puisi ini mengingatkan bahwa ada tugas yang jauh lebih besar di depan: membawa perubahan nyata di tempat di mana agama kerap menjadi alat justifikasi bagi ketidakadilan.
Ketika dihubungkan dengan Festival Toleransi di Galeri Nasional, di mana lukisan “Paus Mencuci Kaki Rakyat Indonesia” karya Denny JA dipamerkan, puisi ini menjadi refleksi kritis atas apa yang sebenarnya terjadi di balik slogan-slogan toleransi dan inklusivitas. Festival ini, yang mungkin dimaksudkan sebagai perayaan nilai-nilai kemanusiaan, pada akhirnya bisa menjadi cerminan dari ironi yang ditunjukkan dalam puisi Madasari. Meski festival ini mengusung semangat toleransi, kita harus bertanya: Apakah toleransi itu benar-benar tercermin dalam tindakan dan kebijakan sehari-hari? Atau, apakah itu hanya menjadi sandiwara lain di atas panggung neraka dunia yang sama, seperti yang dilukiskan dalam puisi ini?
Dengan demikian, “Bapak Paus” bukan hanya sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik sosial yang mendalam, yang menantang kita untuk melihat lebih dalam realitas di sekitar kita. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya melihat keindahan luar dari upacara religius atau festival toleransi, tetapi juga untuk merenungkan makna sebenarnya dari tindakan dan kebijakan yang kita jalani. Okky Madasari, melalui puisi ini, mengingatkan kita bahwa iman dan agama seharusnya membawa keadilan dan kebenaran, bukan menjadi alat untuk menutupi dosa-dosa yang tersembunyi di balik lantunan puja-puji.